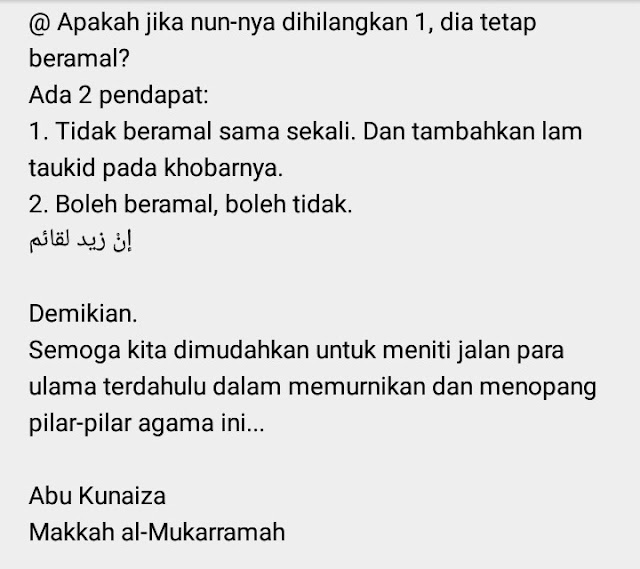Sejak
lama saya bertanya-tanya: "Mengapa mayoritas ulama nahwu beraqidah
mu'tazilah? Apa hubungan antara keduanya?" Ketika saya mencari tahu lebih
dalam, saya temukan beberapa poin berikut:
1. Keduanya bagaikan saudara kembar, karena lahir di waktu dan tempat yang sama, yaitu abad ke 2 hijriyah di Bashrah. Sehingga wajar jika keduanya berhubungan erat.
2. Mu'tazily itu orangnya rasional dan sangat gemar dengan hal yang rasional. Sedangkan nahwu bagi mereka adalah ilmu yang rasional dan bisa menguatkan akal bagi yang mempelajarinya.
3. Pada masa keemasan ilmu nahwu, mu'tazilah adalah satu-satunya manhaj yang diakui pemerintah (sejak khalifah al-Manshur), bahkan adanya hukuman bagi yang tidak sejalan, yang dikenal dengan tragedi al-mihnah.
4. Mu'tazilah butuh nahwu dan balaghah. Karena hanya dengannya mereka bisa mempertahankan hujjah mereka. Ketika mereka temukan ada hal yang mengarah kepada tasybih dalam al-Qur'an, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu berjalan pada prinsip bahasa.
5. Bahasa itu bisa membuat orang kagum. Simak ucapan Zamakhsyari (ulama mu'tazilah) berikut ini:
"aku
melihat saudara kami seagama senang memadukan antara ilmu bahasa dan ilmu
agama, setiap kali mereka datang kepadaku untuk meminta penjelasan suatu ayat,
maka aku singkapkan kepada mereka sebagian hakikat yang ada di balik tabir.
Mereka pun bertambah kagum dan takjub. Hingga mereka merindukan seorang penulis
yang mampu menghimpun semua aspek hakikat tersebut" (al-Kasysyaf: 24).
Apa bukti yang paling menonjol di kitab-kitab mereka bahwasanya mereka bermanhaj mu'tazilah?
Apa bukti yang paling menonjol di kitab-kitab mereka bahwasanya mereka bermanhaj mu'tazilah?
"Hampir tidak kita dapati para ulama nahwu klasik berhujjah dengan hadits, atau sedikit sekali. Karena mereka termasuk ingkar sunnah"
Imam asy-Syafi'i dijuluki dengan ناصر السنة (penolong sunnah) karena beliau menghadapi kaum mu'tazilah yang sedang berkembang di Baghdad ketika itu. Sehingga mereka dikenal dengan kaum yang menolak sunnah atau mentakwilnya.
Mari kita buktikan dengan mengambil beberapa sample kitab:
1. Al-Kitab milik Sibawaih
Di
dalamnya terdapat 1050 syair, 400 ayat al-Qur'an, dan sekitar 4 hadits saja.
2. Al-Muqtadhob milik al-Mubarrid
2. Al-Muqtadhob milik al-Mubarrid
Di
dalamnya terdapat 561 syair, 500 ayat al-Qur'an, dan tidak lebih dari 3 hadits.
3. Al-Masail al-'askariyyah milik Abu Ali al-Farisy
3. Al-Masail al-'askariyyah milik Abu Ali al-Farisy
Di
dalamnya terdapat 113 syair, 68 ayat al-Qur'an, dan tidak ada hadits sama
sekali.
Alasan mereka:
Alasan mereka:
1.
Bolehnya meriwayatkan
hadits dengan maknanya saja.
2.
Kebanyakan perowi adalah
non Arab, sehingga ada kemungkinan terdapat kesalahan bahasa dalam hadits.
3.
Tidak pernah ada contoh
dari ulama sebelumnya.
4.
Banyaknya hadits palsu,
sehingga hadits bukan lagi sumber otentik dan kita cukupkan dengan al-Qur'an
dan syair saja.
Bantahan kami:
1.
Meskipun ada sebagian
ulama yang membolehkan periwayatan hadits dengan makna ketika belum
dibukukannya hadits, namun syaratnya sang perowi harus orang yang paham bahasa
Arab. Akan tetapi mayoritas ulama hadits melarang periwayatan hadits dengan
makna secara mutlak.
2.
Bahkan kebanyakan imam
nahwu adalah non Arab, seperti: Sibawaih dari Iran, Ibnu Jinni dari Romawi,
Zamakhsyari dari Uzbekistan, Ibnu Malik dari Spanyol. Dalam keseharian mereka
tidak berbahasa Arab, namun keilmuan mereka dalam ilmu nahwu dijadikan rujukan
di seluruh penjuru dunia. Dan perlu diingat, untuk menjadi perowi hadits itu
harus melalui persyaratan yang ketat. Contoh kecil saja, ketika Sibawaih hendak
belajar hadits kepada Hammad (ulama hadits), maka Hammad berkata: "bahasa
Arabmu kacau". Maka pergilah Sibawaih kepada Khalil untuk belajar nahwu.
Disini kita ambil pelajaran bahwa untuk menjadi ulama hadits harus memperbagus
ilmu bahasanya.
3.
Alasan ini tidak kuat.
Ulama terdahulu tidak berdalil dengan hadits tidak menjadikan hukumnya haram,
jika kita hendak menjadikan hadits sebagai hujjah dalam nahwu.
4.
Mungkin mereka kurang
piknik. Betapa banyak perowi hadits yang tsiqoh. Jika hadits saja yang begitu
selektif periwayatannya mereka ragukan, bagaimana dengan syair? Betapa banyak
syair yang diubah kata-katanya, karena tidak adanya periwayatan yang jelas.
Jika memang alasan mereka adalah masalah keotentikan, maka mengapa al-Qur'an
mereka tempatkan di nomor 2 setelah syair? Padahal al-Qur'an adalah sumber yang
paling otentik.
Namun
bagaimana hukumnya kita belajar kepada mereka?
Syaikh
Utsaimin dan Syaikh Khudhoir pernah ditanya, bolehkah mempelajari Tafsir
al-Kasysyaf milik Zamakhsyary?
Syaikh
Utsaimin menjawab: "Dalam masalah apa? Zamakhsyari ia seorang mu’tazilah,
ia menamakan orang-orang yang menetapkan sifat Allah, sebagai Hasyawiyah (tidak
bisa dipercaya) atau Mujassimah (berbentuk), dan menyesatkan mereka. Oleh
karenanya bagi siapa saja yang membaca bukunya dalam menafsirkan al-Qur’an agar
berhati-hati dengan pendapatnya dalam masalah sifat-sifat Allah. Namun kitab
tafsir tersebut dari sisi balaghah adalah baik, banyak memberikan manfaat"
Syaikh
Khudhoir menjawab: "Jika tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya
yang tidak sejalan dengan syariah maka hukumnya adalah boleh"
Adapun
kitab-kitab mereka yang hanya khusus membahas ilmu nahwu, maka insya
Allah tidak masalah. Demikian sekilas kita menengok ke masa lalu untuk
dijadikan pembelajaran. Semoga kedepannya kita bisa mencetak ahli nahwu yang
bermanhaj ahli sunnah.
Abu Kunaiza
Riyadh